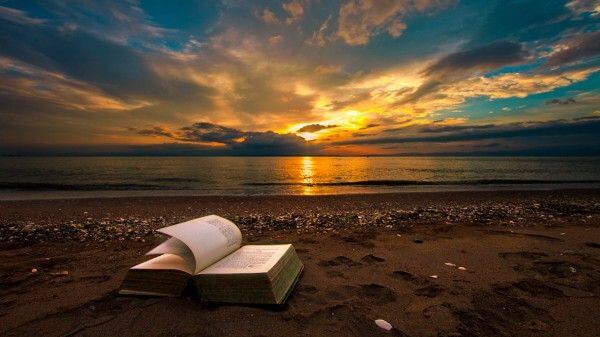Saya dan NU

Ayah dan ibu saya NU, kakek dan nenek saya NU, paman dan bibi saya NU, Uwak dan keluarga besar saya NU. Saya mungkin salah satu dari ribuan kader Muhammadiyah yang dititipkan oleh keluarga NU, karena satu atau dua hal yang akan saya ceritakan dalam catatan ini.
Apakah ini semacam klaim belaka bahwa keluarga besar saya, sebab bukan Muhammadiyah, maka mereka adalah Nahdliyin hanya karena banyak muslim di pedesaan rata-rata begitu? Saya kira tidak. Keluarga besar kami di Limbangan, Garut, Jawa Barat, mengelola sebuah pesantren keluarga yang mengibarkan bendera NU di sana.
Almarhum Kakek saya memasang bendera PPP di masa orde baru, kemudian PKB di zaman Gur Dur, dengan satu kalimat yang ia ungkapkan, “Pan urang mah NU, ngiluna ka ulama.” Katanya, kita kan NU, ikut para ulama. Waktu itu politik belum sekeruh sekarang, tentu saja.
Dalam tradisi keluarga, ziarah adalah hal yang tak bisa saya tinggalkan. Suatu ketika saya bertanya pada nenek saya, mengapa kita perlu pergi ke makam dan berdoa kepada orang-orang yang telah tiada? Nenek menggelengkan kepala. “Kita tidak berdoa kepada mereka, tetapi mendoakan mereka.” Jawabnya.
“Tapi kan berdoa bisa di mana saja, tidak perlu ke makam?” Saya berusaha mendebat nenek waktu itu. Ia hanya tersenyum sambil menggeleng, kemudian menjawab, “Nanti kamu akan mengerti,” katanya, “Makam bukan sekadar tempat untuk mengubur jasad orang yang telah tiada, tetapi tempat menyimpan perasaan orang-orang yang kita cintai. Kita ke sana karena menghargai perasaan itu.” Jawaban nenek ini mengubah cara berpikir saya. Tahun 2012 saya ceritakan di buku Perjalanan Rasa.
Maka ziarah, tahlil, tawasul, dan lainnya adalah tradisi keluarga besar saya yang demikian lekat. Tak bisa saya tinggalkan. “Kalau merasa kurang tenang dalam menghadapi situasi berat, kirim hadiah al-Fatihah saja ke almarhum kakek, lalu ke Mama Abdul Fatah, terus tawasul ke Eyang Jafar Siddiq hingga ke Rasulullah.” Pesan ayah suatu hari. Hadiah dan tawasul jadi cara saya mengenang Kakek, semacam membaca ulang kartu keluarga yang membuat saya perlu selalu mawas diri.
Saat ini, ayah saya adalah Wakil Katib Suriah PWNU Jawa Barat. Uwak saya Wakil Rais Suriah. Tak mengherankan jika kata NU disebut, selalu ada bel berdering dalam diri saya. Karena ada ayah di sana. Ada kenangan tentang kakek. Tapi, bagaimana ceritanya saya jadi kader Muhammadiyah?
Singkatnya, ayah saya yang mengajar filsafat pendidikan Islam di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, mengagumi KH. Miskun Asy-Syatibi karena kedalaman ilmu tafsirnya. Kiai Miskun adalah seorang muallim Muhammadiyah yang ketika itu memimpin Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut.
Dengan berbagai pertimbangan, setelah lulus SD, saya dikirim ke pesantren itu. Saya dititipkan ayah pada Kiai Miskun dengan satu pesan, “Belajar yang baik, supaya hebat seperti Kiai Miskun.” Katanya. Saya mengangguk. Hanya bisa sami’na wa atho’na.
Di pondok, saya tumbuh sebagai pembelajar. Kiai Miskun mengajari santri-santrinya tentang pentingnya memiliki khazanah keilmuan agama maupun sains yang luas. Literasi itu penting. Berpikiran terbuka adalah modal untuk menjelajahi dunia ilmu. Ia mengenalkan konsep ‘hurriyatul fikriyah’ atau kebebasan berpikir selama kita bisa bertanggung jawab dengan argumen yang kokoh, dengan dalil-dalil naqli dan ‘aqli.
Tentu ada tabrakan-tabrakan tradisi ketika saya mondok di Darul Arqam. Tahlil jadi disoal, subuh tak qunut lagi, ziarah harus menemukan rasionalitasnya. Kadang saya berdebat hebat dengan para ustadz di pondok. Di rumah saya harus berdiskusi berlarut-larut lagi dengan ayah. Saya datang ke Limbangan hanya untuk men-challange Kakek ngaji kitab. Almarhum Kakek hanya tersenyum melihat saya baca kitab kuning dengan Arab gundul miliknya, saya coba tafsir dengan gaya Kiai Miskun. “Geuningan Muhammadiyah teh alus, budak jadi pinter.” Komentar Kakek, ternyata Muhammadiyah itu bagus, bikin anakmu (kepada ayah saya) jadi pinter.
Sejak saat itu saya diizinkan memilih dengan argumen saya sendiri. Saya boleh menjadi apa saja dan siapa saja, tak ada satu identitas pun yang perlu saya risaukan atau harus saya bawa. Gelar keluarga tak perlu saya pakai dan perbedaan pendapat akan selalu dihargai selama saya bisa menunjukkan argumennya. Saya selalu jatuh cinta pada Muhammadiyah karena argumen-argumen rasionalnya tentang agama, pilihannya untuk selalu bergerak menuju kemajuan, kulturnya yang demokratis dan egaliter.
Di Muhammadiyah, saya bisa menjadi diri sendiri, mengamalkan nasihat “laisal fatā man yaqūlu hadza abā walakinnal fatā man yaqūlu ha ana dza”. Seorang pemuda bukanlah yang mengatakan ini bapakku atau kakekku, tapi inilah diriku sendiri.
Saya pun berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyarakta, berorganisasi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), menempa diri di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), terus belajar menjadi kader Muhammadiyah. Membangun jalan saya sendiri dengan pikiran progresif. Islam harus bergerak dengan menaklukkan sendi-sendi peradaban: sains, pendidikan, kesehatan, hingga politik. Muhammadiyah mengajarkan saya manajemen dalam menyusun pergerakan ke arah sana.
Suatu ketika Buya Syafii Maarif berpesan bahwa NU dan Muhammadiyah harus bergandengan tangan untuk masa depan bangsa ini. Harus bersatu. Saya tak bisa menahan rasa bahagia dalam dada ketika membaca artikel Buya, hati saya jadi hangat, masa lalu dan masa kini dalam diri saya berdetak. Membunyikan lonceng kenangan sekaligus harapan. Saya mungkin bukan satu-satunya anak NU yang jadi kader Muhammadiyah, tapi ketika itu pesan Buya rasanya buat saya. Saya terpanggil. Terinspirasi. Tentu banyak yang seperti saya.
Kapanpun ada kata NU, ada sesuatu yang menyala-nyala dalam diri saya, tak bisa saya bendung. Seperti hari ini, saat NU merayakan hari lahirnya yang ke-95, ada bagian diri saya yang terpanggil.
Selamat hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95.
Fahd Pahdepie
Kader Muhammadiyah